HUKAMANEWS - Keadilan semestinya menjadi pilar kokoh negara hukum, namun di Indonesia, ia kerap diperlakukan bak komoditas: bisa dibeli, dinegosiasikan, bahkan diperjualbelikan kembali. Praktik suap di ruang pengadilan bukan lagi kejutan, melainkan gejala sistemik yang mengakar. Dalam konteks ini, penaikan gaji hakim—meski diperlukan—belum menyentuh akar persoalan.
Pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., dalam catatan analisis politiknya menegaskan bahwa krisis integritas di lembaga peradilan tidak bisa diselesaikan hanya dengan insentif, tetapi harus melalui reformasi menyeluruh yang menyentuh rekrutmen, etika, dan pengawasan. Berikut catatan lengkapnya.
***
KEADILAN seharusnya menjadi pilar utama peradaban hukum. Namun di Indonesia, keadilan kian tampak sebagai komoditas: bisa dinegosiasikan, diperjualbelikan, bahkan ditawar ulang. Ruang sidang yang semestinya menjadi tempat kebenaran ditegakkan, justru kerap berubah menjadi pasar transaksi perkara.
Fenomena ini bukan hal baru. Nama-nama hakim yang terjerat skandal suap sudah terlalu sering menghiasi media. Sayangnya, publik mulai kehilangan rasa marah. Mungkin karena harapan terhadap tegaknya keadilan yang murni telah lama pupus.
Pemerintah mencoba merespons kegelisahan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024, yang menaikkan gaji hakim secara signifikan, bahkan hingga 280 persen untuk hakim pemula. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kesejahteraan aparatur peradilan.
Namun, pertanyaannya: apakah krisis etika bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan finansial?
Benar bahwa kesejahteraan penting. Hakim yang dibayar layak lebih mungkin bekerja dengan tenang dan profesional. Namun, melihat vonis ringan terhadap para pelaku suap dalam perkara besar seperti kasus Ronald Tannur, kita sadar bahwa akar persoalan jauh lebih dalam.
Contohnya, Zarof Ricar, eks pejabat Mahkamah Agung, menerima suap lebih dari Rp900 miliar, namun hanya dijatuhi hukuman 16 tahun—jauh dari tuntutan jaksa. Lisa Rachmat, pengacara dalam kasus yang sama, mendapat 11 tahun. Bahkan, Meirizka Widjaja, ibu dari Ronald Tannur yang menyuap demi membebaskan anaknya dari kasus pembunuhan, hanya divonis 3 tahun.
Vonis ringan ini diberi pembenaran dengan alasan usia lanjut, ketidaktahuan hukum, hingga belas kasihan. Tapi publik membaca pesan berbeda: bahwa hukum masih belum berdiri tegas dan setara. Jika suap dan korupsi di lembaga yudikatif dihukum ringan, bagaimana mungkin rakyat percaya bahwa pengadilan adalah tempat mereka mencari keadilan?

Kenaikan gaji hakim patut diapresiasi, tapi jangan sampai justru menjadi legitimasi baru untuk menaikkan “tarif” jual beli perkara. Tanpa reformasi menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menjadi plester di luka yang menganga.
Upaya memperbaiki sistem peradilan harus menyentuh akar: reformasi rekrutmen, pendidikan etika, pengawasan berlapis, serta sanksi keras dan konsisten. Sayangnya, lembaga seperti Komisi Yudisial masih kekurangan taji, dan Mahkamah Agung sendiri belum sepenuhnya akuntabel.
Sementara itu, narasi “kemanusiaan” justru digunakan untuk melunakkan hukuman bagi koruptor. Padahal, korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia mencuri masa depan rakyat, menghancurkan layanan publik, dan memperlebar jurang ketimpangan.
Bank Dunia mencatat, pada 2024, sekitar 194 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bocor melalui sogokan dan mafia hukum. Namun, di ruang sidang, para koruptor tetap "dimanusiakan", bukan diperlakukan sebagai perusak bangsa.












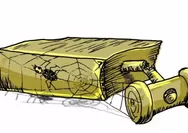


Artikel Terkait
Prabowo dan Taruhan Besar Pemberantasan Korupsi
Premanisme Politik, Ancaman Nyata bagi Demokrasi
Surat Purnawirawan TNI dan Bahaya Makar Terselubung, Negara Tak Boleh Diam!
Peta Baru Kemiskinan Global dan Korupsi yang Mengakar: Saatnya Prabowo Menepati Janji
Pendidikan dan Kesehatan: Pilar Peradaban yang Terabaikan di Tengah Elite Korup dan Kepemimpinan yang Kehilangan Arah