HUKAMANEWS - Gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 yang mengguncang kota-kota besar melahirkan tragedi demokrasi: suara rakyat hanya didengar setelah nyawa melayang. Dari tuntutan “17 plus 8”, satu isu paling panas adalah percepatan RUU Perampasan Aset yang 15 tahun tersandera kepentingan. DPR dan pemerintah kini tergopoh membahasnya, tetapi publik tak mudah percaya. Apakah ini komitmen melawan korupsi atau sekadar manuver meredam amarah?
Pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli, dalam analisis politiknya, menegaskan bahwa tragedi ini bukan sekadar soal undang-undang, melainkan ujian moral elite yang kerap abai pada suara rakyat. Berikut ini catatan lengkapnya.
***
RUU Perampasan Aset yang 15 tahun tertunda kini dibahas usai gelombang demo. Publik menagih: serius lawan korupsi atau retorika politik?
GELOMBANG demonstrasi besar yang berlangsung selama sepekan pada akhir Agustus 2025 mengguncang jalanan di berbagai kota di Indonesia, menyorot tuntutan yang dikenal sebagai “17 plus 8”. Dari sekian banyak aspirasi, satu isu mencuat paling panas adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, beleid yang nyaris 15 tahun tergantung tanpa kepastian.
Menariknya, di tengah tekanan publik yang memuncak, DPR dan pemerintah tiba-tiba menyatakan siap membahasnya. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah RUU ini benar-benar akan menjadi instrumen tegas untuk menumpas korupsi, atau sekadar manuver politik untuk meredam amarah rakyat yang berkobar?
Baca Juga: “Mental Stunting” Pejabat
Sejak pertama kali diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008, RUU ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Akan tetapi, nasibnya terus terombang-ambing dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, dan kini di tangan Prabowo Subianto. Pada masa SBY, pembahasan jalan di tempat. Di era Jokowi, draf sudah diajukan ke DPR pada 2023, tetapi kandas di tengah hiruk-pikuk politik elektoral. Kini, di era Prabowo, desakan publik kembali membuncah, memaksa pemerintah dan DPR menaruhnya kembali di meja pembahasan.
Secara substansi, RUU Perampasan Aset menawarkan terobosan penting. Konsep non-conviction based asset forfeiture memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan meski belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan mekanisme ini, uang rakyat yang dikorupsi dapat segera dipulihkan tanpa harus menunggu proses peradilan yang berlarut-larut.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, sepanjang 2020–2024 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp45,7 triliun, sementara aset yang berhasil dipulihkan hanya sekitar Rp2,5 triliun. Jurang lebar ini menunjukkan betapa mendesaknya instrumen hukum yang lebih efektif. Jika RUU ini disahkan dengan kualitas baik, celah itu bisa tertutup dan efek jera semakin kuat.
Namun, publik tentu tidak ingin RUU ini hanya dikebut seperti revisi UU TNI yang selesai dalam sebulan. Kecepatan boleh jadi penting, tetapi kualitas dan transparansi jauh lebih menentukan dalam penyusunan sebuah undang-undang.
Benturan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan
Ada persoalan krusial yang muncul terkait sinkronisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengharuskan adanya bukti sah dan putusan pengadilan sebelum negara dapat merampas aset. Sebaliknya, RUU ini justru membuka jalan perampasan tanpa menunggu vonis.












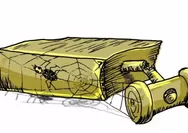


Artikel Terkait
Mafia Skincare, Kosmetik Ilegal, dan Wajah Kusam Penegakan Hukum di Indonesia
Sudewo dan Cermin Retak Empati Pejabat Publik di Era Prabowo
Membaca Wajah 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Antara Euforia Kekuasaan, Elitisme, dan Antiklimaks Reformasi
Menyulam Tenun Kebangsaan, Menjaga Indonesia
Keadilan Fiskal dan Martabat Demokrasi