HUKAMANEWS - Isu lama tentang keabsahan ijazah Presiden Jokowi kembali dipolitisasi. Meski telah berkali-kali dibantah oleh institusi resmi, narasi ini terus dihidupkan dengan aroma provokasi.
Prihatin dengan kondisi ini, pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., dalam tulisan analisis politiknya mengajak publik melihat lebih dalam mengapa fitnah semacam ini terus muncul dan siapa yang diuntungkan dari kegaduhan yang terjadi. Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga mengajak bagaimana kita seharusnya menjaga demokrasi dari erosi nalar dan etika.
***
TUDUHAN ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Ir. Joko Widodo, kembali mencuat, seakan menjadi komoditas musiman yang dihidangkan saat suhu politik meningkat. Isu ini, yang sejatinya telah berkali-kali dibantah dan dijelaskan secara terbuka oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali diangkat dengan narasi seolah-olah ada skandal besar yang ditutup-tutupi. Padahal, institusi akademik yang bersangkutan telah menegaskan: Jokowi adalah alumni resmi Fakultas Kehutanan, dengan skripsi dan rekam jejak akademik yang terdokumentasi.
Namun demikian, tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam: kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat.
Politik yang Kehilangan Substansi
Kita tidak hidup dalam dunia yang kekurangan akses informasi. Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif.
Dalam prinsip hukum dikenal adagium actori incumbit probatio — siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Tuduhan tanpa bukti kuat hanya akan menjadi fitnah, bukan kritik.
Sayangnya, logika politik hari ini kerap tidak berjalan beriringan dengan logika hukum ataupun etika. Tuduhan yang lemah sering justru mendapat panggung lebih luas di media sosial dan kanal-kanal digital, menciptakan distorsi persepsi publik. Politik kehilangan substansi ketika lebih sibuk menyerang personal daripada mengkritisi kebijakan.
Bukan Kritik, Tapi Delusi
Kita bisa menerima bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah harus dikoreksi, dikawal, dan diawasi. Namun, menyerang seorang mantan presiden — siapa pun orangnya — dengan narasi tanpa dasar hukum yang valid, bukanlah praktik oposisi yang sehat. Itu adalah delusi politik, lahir dari dendam dan kegagalan mengartikulasikan agenda perubahan secara konstruktif.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa narasi ini bisa berdampak lebih luas. Ia mengikis kepercayaan terhadap institusi pendidikan, menciptakan keraguan terhadap stabilitas politik nasional, dan pada akhirnya merugikan iklim investasi. Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama.
Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia.












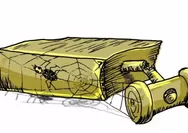


Artikel Terkait
Premanisme Berkedok THR, Ancaman bagi Industri dan Stabilitas Nasional
Reshuffle Kabinet dan Ujian Kredibilitas Pemerintahan Prabowo
Ketika Religiusitas Dijadikan Topeng Kekuasaan; Etika Berbangsa di Persimpangan Jalan
Membantu Gaza, Melupakan Rumah Sendiri, Catatan Kritis untuk Prabowo
Catatan Kritis untuk Presiden Prabowo: Jalan Pintas Impor dan Ancaman terhadap Kemandirian Ekonomi