HUKAMANEWS - Di tengah gemuruh politik yang tak kunjung reda, Indonesia justru melupakan dua fondasi utama peradaban: pendidikan dan kesehatan. Alih-alih memperkuat sistem yang mencerdaskan dan menyehatkan rakyat, negara justru sibuk mempertontonkan retorika tanpa arah.
Pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., dalam catatan analisis politiknya menilai bahwa bangsa yang abai pada kecerdasan dan kesehatan rakyatnya akan terus menjadi penonton dalam panggung global. Ironisnya, menurut mantan Ketua Komisi III DPR ini, saat negara lain berlomba mencetak ilmuwan dan memperluas akses layanan kesehatan, Indonesia malah sibuk berdebat soal subsidi UKT dan pemotongan beasiswa. Menurut Pieter, ini bukan sekadar krisis anggaran, tapi krisis visi berbangsa. Berikut tulisan lengkapnya.
***
TIGA PULUH LIMA tahun yang lalu, dunia nyaris tak melirik Tiongkok. Negara ini dianggap tertinggal, miskin, dan terlalu sibuk dengan urusan dalam negerinya. Namun hari ini, Tiongkok berdiri sebagai kekuatan ekonomi dan politik dunia. Ketergantungan global terhadap manufaktur, teknologi, hingga lembaga pendidikan dan kesehatannya menjadi bukti bahwa kebangkitan peradaban bukan mitos jika dibangun dengan visi jangka panjang dan kebijakan yang konsisten.
Bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki sumber daya alam melimpah, bonus demografi, dan letak geografis strategis. Namun kita belum beranjak jauh. Sering kali terjebak dalam euforia pertumbuhan tanpa menata fondasi negara yang kokoh. Banyak hal besar dibicarakan—dari pembangunan infrastruktur, digitalisasi, hingga pemberantasan korupsi—namun pendidikan dan kesehatan belum sungguh menjadi prioritas pembangunan.
Padahal sejarah negara-negara maju selalu dimulai dari dua pilar utama: pendidikan yang mencerdaskan dan sistem kesehatan yang merata. Tanpa keduanya, pembangunan hanya akan menghasilkan ilusi kemajuan.
Pendidikan dan Kesehatan, Pilar Peradaban yang Terabaikan
Indonesia tidak kekurangan teknologi. Jaringan 5G telah menjangkau berbagai wilayah, dan masyarakat di pelosok pun kini akrab dengan gawai dan media sosial. Namun, kemajuan digital ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Anak-anak lebih fasih bermain TikTok daripada membaca buku. Ruang kelas yang seharusnya menjadi arena diskusi kini digantikan oleh perdebatan kosong di kolom komentar media sosial.
Ini bukan semata persoalan teknologi, melainkan cerminan dari lemahnya pendidikan karakter dan literasi kritis dalam sistem pendidikan kita. Generasi muda tidak dibiasakan untuk berpikir reflektif, mempertanyakan, dan berdialog secara sehat. Akibatnya, mereka mudah terpapar hoaks, gampang dihasut, dan makin apatis terhadap nasib bangsanya sendiri.
Yang lebih mengkhawatirkan, pendidikan tinggi kian menjauh dari rakyat. Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri melonjak tanpa kendali. Sementara itu, anggaran pendidikan dipangkas, dan sejumlah program beasiswa mulai disusutkan. Kampus—yang idealnya menjadi ruang terbuka untuk semua kalangan—perlahan berubah menjadi ruang eksklusif bagi mereka yang berpunya.
Ironisnya, semangat reformasi di sektor pendidikan dan kesehatan justru dibayangi oleh berbagai kasus memprihatinkan: perundungan (bullying) dalam program pendidikan kedokteran, intoleransi di lingkungan akademik, serta diskriminasi dalam layanan kesehatan. Ini bukan sekadar noda dalam catatan kebijakan publik, melainkan alarm keras bagi masa depan bangsa. Karena pada akhirnya, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam setiap pengambilan kebijakan.
Kondisi di sektor kesehatan pun tak jauh berbeda. Pelayanan medis yang layak hanya dapat diakses oleh mereka yang tinggal di kota-kota besar. Di banyak wilayah, puskesmas kekurangan tenaga, rumah sakit minim fasilitas, dan masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Budaya perundungan dalam pendidikan kedokteran turut memperparah krisis ini. Dampak dari bully terhadap profesi dokter sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan kesehatan—baik dari sisi etika, empati, maupun profesionalisme tenaga medis itu sendiri.
Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam indikator pendidikan dan kesehatan, bahkan dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar data statistik, tetapi peringatan serius bagi para pemegang kekuasaan. Pendidikan dan kesehatan bukan persoalan teknis belaka, melainkan penentu arah masa depan bangsa.
Sayangnya, perhatian terhadap kualitas pengajar, infrastruktur pendidikan, hingga pemerataan akses masih jauh dari harapan. Tanpa perbaikan menyeluruh, wacana tentang bonus demografi dan visi “Indonesia Emas 2045” hanya akan menjadi slogan seminar—jauh dari kenyataan yang dihadapi rakyat sehari-hari.












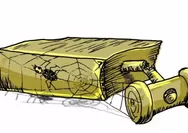


Artikel Terkait
Ketika Megawati Takut pada Bayang-Bayang Jokowi
Prabowo dan Taruhan Besar Pemberantasan Korupsi
Premanisme Politik, Ancaman Nyata bagi Demokrasi
Surat Purnawirawan TNI dan Bahaya Makar Terselubung, Negara Tak Boleh Diam!
Peta Baru Kemiskinan Global dan Korupsi yang Mengakar: Saatnya Prabowo Menepati Janji