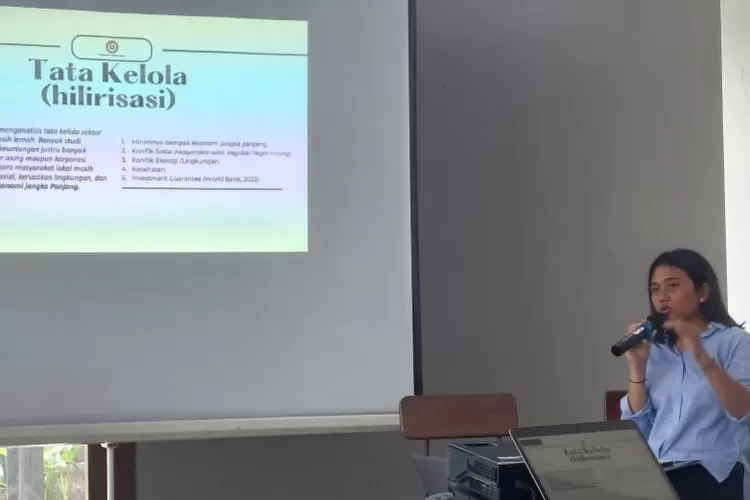HUKAMANEWS - Rampungnya perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) menandai babak baru diplomasi dagang Indonesia. Pemerintah optimistis perjanjian ini akan membuka akses pasar dan investasi. Namun, di balik euforia tersebut, tersimpan kegelisahan tentang satu sektor yang kini sangat strategis: mineral kritis.
Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan bahwa IEU CEPA bukan sekadar perjanjian dagang biasa. Dalam kertas analisis bertajuk “IEU CEPA: Kendali Mineral Kritis Indonesia di Tangan Siapa?”, IGJ menilai sejumlah ketentuan justru menguji batas kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.
“Ketentuan dalam IEU CEPA, terutama di Bab Investasi serta Energi dan Bahan Baku, sangat membatasi ruang kebijakan nasional,” ujar Koordinator Program IGJ, K. Audina Permana Putri, dalam media briefing di Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Indonesia tak lagi leluasa mewajibkan transfer teknologi, kandungan lokal, atau kemitraan dengan pelaku domestik. Bahkan relaksasi izin tenaga kerja asing disepakati secara mengikat,” lanjutnya.
Baca Juga: Bertahan di Tengah Banjir dan Krisis Pasokan, SPPG Aceh Andalkan Menu Lokal dan Briket Batu Bara
Padahal, mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan bauksit adalah fondasi hilirisasi dan transisi energi. Pemerintah selama ini mendorong pengolahan di dalam negeri demi nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Masalahnya, ambisi tersebut berhadapan dengan prinsip liberalisasi yang ketat dalam IEU CEPA.
Audina menilai sektor mineral kritis kini berada di persimpangan. “Di satu sisi, Indonesia ingin memperkuat hilirisasi. Di sisi lain, ruang kebijakan itu justru dipersempit oleh komitmen internasional yang terlalu jauh,” katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif IGJ. Ia menyoroti lemahnya posisi tawar Indonesia dalam banyak perjanjian dagang. “Selama ini, manfaat ekonomi yang dijanjikan sering kali tidak sebanding dengan risiko sosial dan lingkungan yang harus ditanggung,” ujarnya. “Perjanjian dagang belum tentu otomatis memperbaiki tata kelola, apalagi jika prosesnya minim transparansi.”
IGJ mencatat, keuntungan sektor mineral kritis selama ini lebih banyak dinikmati investor asing dan korporasi transnasional. Sebaliknya, masyarakat lokal kerap berhadapan dengan konflik sosial, degradasi lingkungan, serta manfaat ekonomi jangka panjang yang terbatas. Tanpa pembenahan kebijakan internal, liberalisasi justru berpotensi memperdalam ketimpangan.
Pandangan kritis juga datang dari kalangan peneliti. Muhamad Aryanang Isal, Koordinator Program Bisnis dan HAM IGJ, menilai perjanjian dagang modern kerap membawa “ancaman lama” terhadap kedaulatan negara. “Mekanisme perlindungan investasi dan potensi gugatan internasional bisa menciptakan regulatory chill. Pemerintah menjadi ragu menerbitkan kebijakan progresif karena khawatir digugat investor,” katanya.
Menurut Aryanang, risiko ini nyata di sektor pertambangan. Kebijakan lingkungan atau penghentian izin tambang, meskipun sah secara hukum nasional, dapat ditafsirkan merugikan investor dan berujung gugatan bernilai besar. Bebannya bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga keuangan publik.
Karena itu, IGJ menilai pemerintah perlu menata ulang prioritas. Pembenahan tata kelola mineral kritis, iklim investasi yang berkeadilan, serta peta jalan industrialisasi dari hulu ke hilir semestinya menjadi prasyarat. “Indonesia perlu kuat di dalam negeri terlebih dahulu, sebelum mengikat diri pada perjanjian internasional yang membatasi ruang gerak,” kata Audina.
Lebih jauh, pemerintah diingatkan agar tidak memandang perjanjian perdagangan semata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Dampaknya harus dilihat secara menyeluruh, termasuk pada kedaulatan energi, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan nasional jangka panjang.