Tragedi ini seharusnya menyadarkan semua pihak bahwa demokrasi bukan pesta lima tahunan, melainkan ruang hidup sehari-hari. Ia harus dijaga dengan hukum yang adil, politik yang bermoral, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Jika tidak, sejarah akan terus menagih harga mahal: nyawa dan perpecahan.
Kematian Affan harus menjadi titik balik. Jangan biarkan ia sekadar menjadi angka dalam laporan. Dari tragedi itu, seharusnya lahir kesadaran kolektif bahwa negara tidak boleh abai pada nyawa rakyatnya sendiri. Kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan kehancuran.
Agustus kelabu telah berlalu. Kini saatnya menyulam kembali tenunan kebangsaan yang sempat koyak. Bukan dengan retorika kosong, tetapi dengan langkah nyata: menghentikan arogansi, membenahi kebijakan, dan membuka ruang dialog yang jujur.
Suara rakyat adalah penopang demokrasi. Persatuan adalah napas bangsa. Mari kita rawat keduanya, sebab hanya dengan itu Indonesia bisa tetap berdiri tegak. Mari kita jaga Indonesia.***












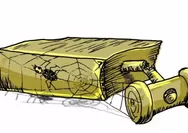


Artikel Terkait
Mengukur Kemiskinan, Melupakan Kemanusiaan: Paradoks Statistik dan Realitas Rakyat
Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Ketika Jalan Pintas Kekuasaan Menelikung Etika Hukum
Mafia Skincare, Kosmetik Ilegal, dan Wajah Kusam Penegakan Hukum di Indonesia
Sudewo dan Cermin Retak Empati Pejabat Publik di Era Prabowo
Membaca Wajah 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Antara Euforia Kekuasaan, Elitisme, dan Antiklimaks Reformasi