HUKAMANEWS - Di tengah suhu politik yang kembali memanas, dua isu besar mencuat dan menyedot perhatian publik: dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kembali diungkit, serta wacana pencopotan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mulai digaungkan sejumlah pihak. Kedua isu ini mencerminkan betapa demokrasi di Indonesia tengah diuji, bukan hanya oleh dinamika politik elite, tetapi juga oleh erosi rasionalitas dalam ruang publik.
Dalam analisisnya, pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zukifli, SH., MH., menyebut bahwa demokrasi tanpa kedewasaan publik dan penghormatan terhadap konstitusi hanya akan menghasilkan kebisingan, bukan perbaikan. Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, yang kita hadapi hari ini bukan sekadar persoalan hukum atau etika, tetapi soal arah masa depan bangsa: apakah kita masih percaya pada demokrasi yang beradab, atau justru kembali tergoda oleh jalan pintas politik yang menyesatkan. Berikut catatan lengkapnya.
***
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya mengambil langkah hukum untuk merespons tudingan ijazah palsu yang terus mengemuka dalam ruang publik. Rabu pagi, 30 April 2025, Jokowi mendatangi langsung Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya guna melaporkan pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk menghentikan penyebaran informasi yang dinilai tidak berdasar dan merusak kredibilitasnya.
Diketahui, telah lebih dari satu dekade, sosok Joko Widodo menjadi wajah utama dalam lanskap politik Indonesia. Dari seorang Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden dua periode, jalan politik Jokowi tidak pernah benar-benar lepas dari kritik, bahkan tuduhan. Salah satu isu yang terus bergulir hingga hari ini—meski telah berkali-kali dibantah—adalah tudingan ijazah palsu.
Isu ini tidak muncul sekali dua kali. Ia berulang, seperti gema yang enggan reda meski telah dijawab tuntas oleh lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, hingga pengadilan. Universitas Gadjah Mada telah mengonfirmasi bahwa Jokowi adalah alumninya. KPU dan lembaga hukum telah menyatakan tidak ada pelanggaran administratif. Namun, sebagian pihak tampaknya tetap memilih untuk tidak percaya. Ini bukan lagi sekadar soal verifikasi, tetapi soal bagaimana narasi dibentuk dan disebarkan di ruang publik.
Dalam demokrasi, publik memang berhak mempertanyakan integritas pemimpinnya. Namun, ketika sebuah tuduhan tanpa bukti dibiarkan terus berkembang, bahkan setelah dijelaskan melalui proses hukum dan lembaga resmi, maka demokrasi justru terancam oleh kebisingan yang tidak sehat. Dalam istilah Noam Chomsky, ini bukan lagi wacana kritis, tetapi propaganda yang menyasar persepsi dan emosi publik.
Apalagi di era digital saat ini, di mana fakta sering kalah cepat dari hoaks, dan opini lebih cepat viral ketimbang klarifikasi. Isu seperti ijazah palsu menjadi alat politik yang murah, namun berdampak besar. Ia menyasar hal yang paling mendasar dalam kepemimpinan: kepercayaan. Dan saat kepercayaan terhadap institusi mulai goyah, kita patut waspada. Demokrasi bisa tergelincir ke dalam kekacauan informasi, di mana suara keras lebih didengar daripada suara yang benar.
Namun, ini bukan satu-satunya ujian. Desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden oleh sekelompok purnawirawan TNI menambah rumit dinamika demokrasi kita. Usulan itu—meski disampaikan dalam bahasa konstitusional—pada dasarnya berpotensi menjadi preseden yang membahayakan prinsip dasar demokrasi: mandat rakyat.
Gibran memang lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Ketua MK saat itu terbukti melanggar etik karena tidak mengundurkan diri saat memimpin sidang yang menyangkut keponakannya sendiri. Namun, etik bukanlah hukum. Dan putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada ruang dalam konstitusi yang memungkinkan pemakzulan seorang wakil presiden hanya karena publik tidak puas terhadap proses pencalonannya.
Usulan mencopot Wapres melalui MPR adalah langkah berbahaya yang bisa menghidupkan kembali logika kekuasaan sebelum Reformasi: logika konsensus elite, bukan suara rakyat. Kita pernah hidup dalam sistem di mana segelintir orang menentukan masa depan bangsa. Kita sepakat untuk berubah sejak 1998, memberikan hak pilih langsung kepada rakyat. Kembali ke mekanisme pencopotan yang tidak diatur dalam UUD 1945 bukan hanya ilegal, tapi juga amnesia sejarah.
Demokrasi kita memang tidak sempurna. Banyak hal yang perlu dibenahi—dari kualitas putusan lembaga hukum, integritas pejabat publik, hingga literasi politik masyarakat. Namun, jalan menuju demokrasi yang matang tidak bisa ditempuh dengan melompat pagar konstitusi. Seburuk apa pun hasil pemilu, jalan koreksi harus tetap dalam kerangka hukum dan etika yang sah.
Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan etika dengan tindakan inkonstitusional. Etika memang penting, tetapi tidak boleh menjadi justifikasi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Jika tidak, kita justru akan membuka jalan bagi kekacauan yang lebih besar: kekuasaan tanpa kepastian hukum.
Tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi dan usulan pencopotan Gibran adalah dua sisi dari tantangan yang sama. Demokrasi kita sedang diuji: apakah kita mampu menahan godaan populisme emosional dan tetap berpijak pada hukum dan akal sehat?
Jika ruang publik terus diisi dengan kecurigaan tanpa dasar, dan jika elite politik kembali memaksakan kehendaknya atas nama “perbaikan”, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara. Padahal, yang sedang kita pertaruhkan bukan hanya jabatan, melainkan masa depan Republik ini.












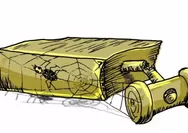


Artikel Terkait
Ketika Religiusitas Dijadikan Topeng Kekuasaan; Etika Berbangsa di Persimpangan Jalan
Membantu Gaza, Melupakan Rumah Sendiri, Catatan Kritis untuk Prabowo
Catatan Kritis untuk Presiden Prabowo: Jalan Pintas Impor dan Ancaman terhadap Kemandirian Ekonomi
Ijazah Jokowi dan Cermin Politik Kita
Menakar Tuntutan Purnawirawan TNI terhadap Gibran dan Pertaruhan Marwah Demokrasi